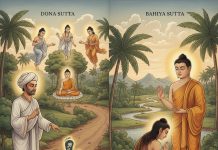UKetika kemudian ia berjumpa dengan Buddhadharma, kisah Pangeran Siddharta terasa mengguncangnya: seolah ada pembenaran untuk dorongan lamanya meninggalkan dunia rumah tangga. Namun pada saat yang sama, muncul keraguan mendalam—keraguan yang bukan sekadar tentang memilih jalan, tetapi tentang bagaimana memahami dukkha, cinta, dan tanggung jawab dalam terang Dharma. Jalan pembebasan perumahtangga bukan sebuah utopia.
Jalan Pembebasan di Tengah Hidup Perumahtangga:
Relasi sebagai Jalan, Bukan Belenggu
Oleh Eko Nugroho R*
Pendahuluan
Di antara mereka yang menapaki jalan Buddhadharma. Tak jarang muncul suatu dorongan awal yang kuat untuk meniru jejak Pangeran Siddharta. Meninggalkan rumah, menanggalkan ikatan keluarga, dan menempuh Nihsaraṇa secara radikal. Kisah agung itu menggugah imajinasi. Seolah pembebasan akan lebih dekat bila kita berani memutus semua dahan keduniawian. Namun realitas batin tidak selalu sesederhana alur naratif. Sebaliknya jalan pembebasan perumahtangga juga bukan ilusi.
Sering kali, pemula hanya melihat satu fragmen sejarah. Siddharta meninggalkan Yasodhara. Yang luput dari jangkauan penglihatan ialah kedalaman hubungan mereka. Hubungan yang telah teranyam dalam banyak kelahiran sepanjang kalpa. Mereka bukan pasangan yang terjalin seketika. Melainkan para teman handal yang saling menopang dalam perjalanan menuju Penggugahan. Kepergian Siddharta bukan penolakan. Melainkan buah kematangan batin yang telah dipupuk dari kehidupan-kehidupan lampau. Disertai pengertian yang jernih dari Yasodhara sendiri.
Kisah Sahabat: Aspirasi, Trauma, dan Kebingungan Jalan
Kerentanan aspirasi yang sama muncul dalam kisah seorang sahabat dalam komunitas meditasi. Sejak muda ia memandang kehidupan rumah tangga sebagai sesuatu yang rapuh dan penuh kesia-siaan. Ia tumbuh dalam bayang-bayang kegagalan pernikahan di sekitar dirinya. Hal ini menanam benih trauma dan penolakan terhadap ikatan emosional yang mendalam. Ketika sang ibu memintanya untuk menikah, ia menerima bukan karena dorongan hati. Melainkan demi memenuhi harapan keluarga. Tahun-tahun berjalan, ia menjalani pernikahan. Menjadi ayah, dan menunaikan peran-peran yang muncul dalam aliran hidup. Namun di dalam batin, tetap ada desir yang samar. Sebuah kerinduan untuk melepaskan diri dari segala belenggu. Untuk menempuh jalan sunyi tanpa ikatan.
Ketika kemudian ia berjumpa dengan Buddhadharma. Kisah Pangeran Siddharta terasa mengguncangnya. Seolah ada pembenaran untuk dorongan lamanya meninggalkan dunia rumah tangga. Namun pada saat yang sama, muncul keraguan mendalam. Keraguan yang bukan sekadar tentang memilih jalan. Akan tetapi tentang bagaimana memahami dukkha, cinta, dan tanggung jawab dalam terang Dharma.
Baca juga: Ian Stevenson 40 Tahun Menyusuri Jejak Reinkarnasi
Perspektif Buddhadharma dan Psikologi Humanis
Di sinilah perspektif Buddhadharma dan psikologi humanis saling melengkapi. Aspirasi pembebasan yang tidak ditopang oleh pengenalan diri yang jujur. Sering kali berubah menjadi bentuk halus dari penghindaran. Dalam psikologi humanis, terutama melalui pemikiran Carl Rogers (1961). Proses pendewasaan batin menuntut keberanian untuk hadir apa adanya. Kejujuran terhadap perasaan sendiri, penerimaan tanpa syarat (unconditional positive regard), dan keterbukaan untuk menyentuh inti pengalaman diri. Tanpa menyangkalnya.
Rogers menyebut kecenderungan ini sebagai dorongan alami menuju aktualisasi diri. Sebuah gerak batin yang hanya dapat muncul dari keaslian dan penerimaan mendalam atas kondisi diri. Dalam horizon yang sama. Maslow (1968) menekankan bahwa kebutuhan aktualisasi diri tidak dapat dicapai melalui pelarian. Tetapi melalui keberanian menghadapi pengalaman manusiawi dengan penuh kesadaran. Dalam konteks ini. Aspirasi pembebasan tidak selalu harus tampil sebagai bentuk penolakan terhadap kehidupan rumah tangga. Kerap kali, bagi praktisi masa kini, jalan itu justru menuntut transformasi batin yang lebih halus. Yakni mengalihkan dorongan untuk “meninggalkan” menjadi kesiapan untuk “menghadir”. Jika Nekkhamma muncul sebagai ‘dorongan untuk bebas dari mencengkeram.’ Maka kebebasan itu dapat berkembang bukan dengan cara menjauhi relasi yang telah terjalin. Melainkan melalui perubahan cara kita menjalani hidup bersama.
Justru ketika seseorang tergugah oleh ideal pembebasan, muncul risiko salah langkah. Seperti menjadi dingin, tampak tak terjamah oleh perasaan, seolah welas asih tak relevan lagi. Padahal, jika aspirasi pembebasan tidak diimbangi Karuṇā dan Kewaskitaan. Ia akan mudah menjelma menjadi bentuk baru dari kecemasan dan kelesah (kilesa). Hal yang berujung penolakan (dosa), sebuah dukkha yang terselubung. Perspektif psikologi humanis membantu menegaskan bahwa kehangatan, kehadiran autentik, dan penerimaan adalah fondasi relasi yang sehat. Sekaligus juga fondasi untuk transformasi spiritual (Cain, 2016).
Transformasi Aspirasi melalui Catur-Apramāṇa
Pada titik inilah ajaran Catur-Apramāṇa menjadi penuntun yang gamblang untuk jalan pembebasan perumahtangga. Mettā adalah hati yang hangat, yang secara aktif mengharapkan dan mengupayakan kebahagiaan bagi yang lain. Karuṇā adalah keberanian untuk hadir di mana ada penderitaan—bukan berlari menjauh darinya. Muditā adalah kemampuan merayakan kebahagiaan orang terdekat—pasangan, anak, keluarga—tanpa tersentuh iri atau penghindaran. Upekkhā adalah keseimbangan dan kesetaraan batin yang membuat kita mampu melihat dukkha tanpa hanyut olehnya, baik dukkha kita sendiri maupun dukkha pasangan.
Keempatnya bukan ideal abstrak; justru semuanya berdenyut paling kuat dalam relasi sehari-hari. Buddhadharma sendiri menegaskan bahwa ketika seseorang menemukan sahabat yang selaras, yang bisa diajak maju bersama, seharusnya ia berjalan bersamanya. Dhammapada 328 menuliskan:
“Jika engkau menemukan seorang sahabat bijaksana yang hidup selaras dan berperilaku luhur, hendaklah engkau berjalan bersamanya dengan gembira dan penuh perhatian, mengatasi segala bahaya.” (Dhp 328)
Kutipan ini bukan sekadar ajakan literal, melainkan penjelasan halus bahwa sebuah relasi dapat menjadi lahan latihan spiritual. Pasangan—yang berbagi suka-duka kita—dapat menjadi mitra handal (kalyanamitra), seorang kalyāṇamitra yang membantu kita mematangkan keberanian untuk menghadapi dukkha sendiri. Seperti dijelaskan dalam Itivuttaka 17 tentang peran para sahabat bajik:
“Para kalyāṇamitra adalah seluruh dari kehidupan suci.” (Iti 17)
Memandang pasangan sebagai kalyāṇamitra bukan berarti menyepelekan konflik atau perbedaan; tetapi melihat bahwa melalui relasi itulah kita belajar mengendurkan genggaman, menumbuhkan kejernihan, dan mempraktikkan cinta yang bebas dari tuntutan.
Berdamai dengan Relasi: Dari Penghindaran Menuju Kehadiran
Samsara di ruang hidup saat ini hanya berlangsung sekejap; namun dalam sekejap itu, kita punya kesempatan untuk menumbuhkembangkan Bodhicitta dalam bentuk yang paling konkret: kesediaan untuk hadir, menyokong, dan berjalan bersama. Keintiman bukan penghalang pembebasan—ia dapat menjadi ladang praktik untuk melihat Sunyata dalam relasi: bahwa tidak ada satu pun yang benar-benar “milikku,” dan justru dari kejernihan ini tumbuh kelembutan yang tak menuntut.
Dalam suasana batin seperti ini, transformasi tidak selalu berarti mengubah dunia luar, tetapi mengubah cara berpijak. Psikologi humanis menyebutnya sebagai proses menjadi manusia yang utuh—yang mampu menghadapi dukkha dengan keberanian, mencintai tanpa kehilangan diri, dan menata batas-batas dengan penuh welas asih.
Jalan Pertapaan: Bukan Jaminan Bebas Dukkha
Sering muncul anggapan bahwa jika seseorang memilih jalan pertapaan, maka seluruh persoalan duniawi akan sirna begitu saja. Namun sejarah dan kenyataan menunjukkan bahwa meninggalkan rumah bukan berarti meninggalkan dukkha. Bahkan para biksu pun kerap berhadapan dengan godaan, tantangan batin, dan kondisi yang dapat menggoyahkan tekad.
Dalam Vinaya dan berbagai kisah Buddhadharma, banyak contoh yang memperlihatkan bahwa kehidupan pertapaan tidak steril dari persoalan duniawi. Para biksu bisa tersandung oleh godaan harta, kedudukan dalam komunitas, atau relasi yang tidak tertata. Godaan sensual, konflik internal sangha, atau ambisi halus kadang justru muncul lebih kuat ketika seseorang berada dalam lingkungan yang diasumsikan suci.
Bahkan Buddha sendiri menghadapi fitnah dan tuduhan, seperti kisah Ciñcā Māṇavikā, yang menuduh Beliau menghamilinya. Udāna 4.8 mencatat bagaimana Buddha tetap diam dan tidak bereaksi, dan kebenaran akhirnya terungkap ketika kain penyangga yang disembunyikan Ciñcā terlepas. Kisah ini menunjukkan bahwa sekalipun sudah mencapai Penggugahan, tantangan dunia tidak lenyap; yang berubah adalah cara seseorang menanggapinya.
Contoh Kasus Kontemporer
Sebagai pembanding kontemporer, sejumlah kasus di Thailand beberapa tahun terakhir menunjukkan kenyataan serupa. Bahwa Sangha pun tidak kebal terhadap godaan duniawi. Misalnya, kasus penggelapan dana di Wat Rai Khing yang melibatkan jutaan baht (Kompas, 17 Mei 2025). Skandal pemerasan seksual dan aliran dana yang menyeret beberapa biksu senior (Bangkok Post, 2025). Serta penyalahgunaan dana amal di Wat Phra Bat Nam Phu yang memicu proses hukum terhadap kepala viharanya (Thai Examiner, 2025).
Contoh-contoh ini tidak dimaksudkan untuk menilai Sangha, melainkan untuk menegaskan bahwa arus samsara dapat menggoyahkan siapa pun bila daya tahan batin dan kewaskitaan belum matang. Semua ini menggarisbawahi bahwa Jalan pertapaan meskipun dapat menjadi medan latihan yang dalam, tetapi bukan jalan pintas menuju kebebasan. Tanpa daya tahan batin, kewaskitaan, dan karuṇā, seseorang bisa saja runtuh di tengah jalan.
Di tengah kenyataan bahwa bahkan kehidupan pertapaan pun tidak bebas dari arus samsara, kita juga melihat sisi lain yang melengkapi gambaran ini: bahwa kehidupan rumah tangga bukanlah penghalang bagi Penggugahan. Sutta-sutta menyimpan banyak contoh kisah upāsaka dan upāsikā yang tetap menjalani hidup keluarga namun mencapai tingkat kesucian.
Teladan Awam dari Masa Lalu
Anāthapiṇḍika—penyokong Jetavana—digambarkan sebagai seorang Sotāpanna yang tetap mengelola rumah besar dan tanggung jawab sosialnya (SN 55.26; AN 7.50). Visākhā Migāramātā, seorang ibu dari banyak anak, juga disebut mencapai tingkat yang sama sejak usia muda, sambil tetap aktif menata rumah tangga dan mendukung Sangha (AN 8.43; Vinaya Mahāvagga VIII). Citta Gahapati bahkan mencapai tingkat Anāgāmī—pencapaian tinggi kedua sebelum Arahat—tanpa meninggalkan perannya sebagai kepala keluarga dan pengusaha (SN 41; AN 8.23). Demikian pula Hatthaka Āḷavaka, pemimpin komunitas yang dikenal karena kehangatan dan welas asihnya, hidup sebagai Sotāpanna sembari memikul tanggung jawab publik dan keluarga (AN 3.127; AN 8.24). Mahānāma Sakya, pejabat publik sekaligus kerabat Buddha, juga digambarkan mencapai tingkat Ariya sambil tetap menjalankan perannya dalam masyarakat (SN 55.21–40; AN 11.12).
Kisah-kisah ini menegaskan bahwa bentuk luar kehidupan, baik rumah tangga atau pertapaan. Bukanlah penentu kemajuan batin. Karena yang menentukan adalah kedalaman Kewaskitaan, ketulusan Karuṇā, dan kemampuan melihat Sunyata dalam menghadapi apapun. Dengan demikian, bagi banyak praktisi modern, rumah tangga dapat menjadi ladang latihan yang subur. Tempat di mana Bodhicitta tumbuh melalui kehadiran, kejujuran, dan cinta kasih yang matang. Kesadaran ini membantu menetralkan romantisasi terhadap kehidupan pertapaan. Ia juga membuka ruang pemahaman. Bahwa latihan spiritual sejati terletak pada kualitas kehadiran, bukan pada bentuk luar.
Penutup: Jalan Pulang Menuju Kehadiran yang Lebih Lapang
Pada akhirnya, pergulatan sahabat ini mengungkapkan sesuatu yang universal: bahwa jalan spiritual tidak pernah terpisah dari kehidupan yang sedang kita jalani. Nekkhamma tidak selalu berarti meninggalkan rumah; kadang berarti ‘meninggalkan pola lama yang dibangun oleh luka.’ Karuṇā (keberaanian untuk hadir di mana ada penderitaan) kadang muncul bukan dalam langkah menjauh, tetapi dalam keberanian untuk tetap tinggal. Dan Mettā (niat bajik) menemukan bentuk paling indahnya dalam kehangatan sederhana: secangkir teh bersama pasangan, obrolan yang jujur, atau kesediaan mendengarkan ketika hari terasa berat. Kehadiran yang tidak mengembangkan cinta dan bukan kemelekatan adalah bagian dari jalan pembebasan perumahtangga.
Seperti sungai yang tetap mengalir meski melalui bebatuan, aspirasi pembebasan dapat menemukan bentuk yang lebih luas dan lembut ketika dialirkan melalui welas asih. Transformasinya bukan dari rumah menuju hutan, tetapi dari ketakutan menuju keterbukaan. Dari penghindaran menuju kehadiran. Dari ideal yang kaku menuju cinta yang matang.
Ketika aspirasi pembebasan diresapi oleh Kewaskitaan dan Karuṇā, ia tidak membawa kita menjauh dari manusia lain, tetapi menuntun kita pulang ke hati yang lebih lapang. Dengan demikian, apa yang dulu tampak sebagai dilema—antara meninggalkan dan tinggal—berubah menjadi perjalanan untuk belajar hadir secara lebih selaras, lebih ringan, dan lebih penuh cinta. Inilah hakikat jalan pembebasan perumahtangga.
*Peneliti Institut Nagarjuna
Bacaan Lanjutan untuk Jalan Pembebasan Perumahtangga
- (T.t.). Dhammapada(terjemahan bahasa Indonesia). Diakses dari https://dhammacitta.org
- (T.t.). Itivuttaka(terjemahan bahasa Indonesia). Diakses dari https://dhammacitta.org
- Lembaga Tipitaka Indonesia. (T.t.). Tipitaka: Sutta Pitaka(terjemahan Indonesia). Jakarta: Lembaga Tipitaka Indonesia.
- Rogers, C. R. (1961). On becoming a person: A therapist’s view of psychotherapy. Houghton Mifflin.
- Maslow, A. H. (1968). Toward a psychology of being(2nd ed.). Van Nostrand.
- Cain, D. J. (2016). Humanistic psychotherapies: Handbook of research and practice(2nd ed.). American Psychological Association.