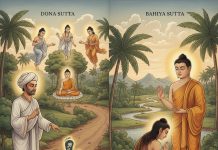Secara meteorologis bencana ini dipicu oleh hujan ekstrem yang turun tanpa jeda. Dan sistem atmosfer kompleks yang berkaitan dengan siklon tropis. Namun interaksi antara faktor alam dan manusia adalah yang memperparah dampaknya. Para ahli lingkungan dan meteorologi menekankan. Bahwa kerusakan hutan dan ekosistem hulu sungai mempercepat limpasan air, memperlemah daya serap tanah, dan memicu banjir serta longsor. Dengan dampak yang jauh lebih mematikan (KLHK, 2022; WALHI, 2023). Ini seharusya menjadi cermin krisis bahwa kesadaran ekologis kita masih rendah.
Tinjauan Kritis Bencana Aceh–Sumut: Membaca Krisis Ekologis dengan Buddhadharma dan Falsafah Jawa
Oleh Eko Nugroho R. (Institut Nagarjuna)
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat. Terjadi pada akhir November–Desember 2025 lalu. Merupakan bencana yang telah menorehkan luka besar dalam kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Data terkini menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 jiwa telah meninggal dunia. Dengan ribuan lainnya terluka dan ratusan ribu mengungsi akibat bencana ini. BNPB memperbarui angka korban menjadi 1.053 jiwa per 16 Desember 2025. Dengan kerusakan rumah, infrastruktur, dan lingkungan yang sangat luas (BNPB, 2025; WALHI, 2023; Kompas.com, 2025).
Fenomena ini memunculkan pertanyaan lebih dalam. Mengapa tragedi ekologis seperti ini terus berulang? Apa maknanya jika kita membaca kejadian ini bukan hanya sebagai “peristiwa alam.” Akan tetapi sebagai cermin krisis kesadaran ekologis.
Bencana Alam Bukan Azab Tetapi Cermin Krisis Kesadaran
Secara meteorologis, bencana ini dipicu oleh hujan ekstrem yang turun tanpa jeda. Dan sistem atmosfer kompleks yang berkaitan dengan siklon tropis. Namun interaksi antara faktor alam dan manusia adalah yang memperparah dampaknya. Para ahli lingkungan dan meteorologi menekankan. Bahwa kerusakan hutan dan ekosistem hulu sungai mempercepat limpasan air, memperlemah daya serap tanah, dan memicu banjir serta longsor. Dengan dampak yang jauh lebih mematikan (KLHK, 2022; WALHI, 2023).
Deforestasi, ekspansi perkebunan besar (minyak sawit, pertambangan, dan izin lahan lainnya) memperparah dampak bencana. Karena hilangnya vegetasi yang semestinya menahan aliran air, mengurangi erosi, dan memperlambat limpasan hujan berat. Baik ke lembah maupun sungai. Kerusakan ekologis masif ini bahkan disebut berdampak “tingkat kepunahan” pada habitat satwa langka seperti orangutan Tapanuli. Populasi kritis yang hidup di hutan utara Sumatera kini makin terancam (WALHI, 2023; KLHK, 2022).
Fenomena ini bukan sekadar “aksentuasi cuaca ekstrem.” Akan tetapi akumulasi dari perjalanan panjang. Di mana tutupan hutan hilang, lahan dirambah, dan sumber daya alam diubah untuk kepentingan jangka pendek. Dalam konteks ini, bencana menunjukkan apa yang disebut oleh para praktisi Buddhadharma sebagai keliru mengerti (avijjā). Kesadaran yang memisahkan manusia dari jaringan hidup yang saling menopang. Serta hilangnya pengakuan terhadap kesalingketergantungan (iddapaccayatā) (SN 12.1 – Paṭiccasamuppāda Sutta).
Etika Ekologis dalam Kesalingketergantungan
Dalam Buddhadharma, ajaran paṭiccasamuppāda (iddapaccayatā) menegaskan. Bahwa segala fenomena muncul dan bertahan melalui jaringan sebab-kondisi yang saling bergantung. “Jika ini ada itu ada, jika ini muncul itu muncul; jika ini tak ada, itu pun tak ada, jika ini hilang itu pun hilang.” Dan tidak ada satu pun entitas yang berdiri sendiri. Ketika manusia merusak hutan, sungai, dan tanah, tindakan tersebut bukan hanya merugikan alam. Tetapi juga merusak manusia itu sendiri, lantaran kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan alam tempat kita berpijak. (SN 12.1 – Paṭiccasamuppāda Sutta; Kaza & Kraft, 2000).
Etika ekologis Buddhadharma mengingatkan bahwa tindakan manusia terhadap alam adalah bagian dari karma. Sekalipun istilah karma bukan “hukum moral”, ia merujuk pada dampak moral dari tindakan yang saling berkaitan dan berimbas pada semua makhluk hidup. Ketidaksadaran terhadap iddapaccayatā membawa manusia pada gaya hidup yang fragmentaris. Gaya hidup yang hanya melihat dunia sebagai “sumber daya” bukan sebagai komunitas kehidupan yang perlu dirawat. (MN 135 – Cūḷakammavibhaṅga Sutta; Loy, 2010).
Memayu Hayuning Bawono, Gotong Royong Kosmis dan Akar Kedalaman Spiritualitas
Dalam falsafah Jawa, gagasan memayu hayuning bawono merangkum etika hidup yang holistik: memperindah dan merawat keseimbangan dunia sebagai wujud tanggung jawab batin manusia. Ini bukan sekadar ideal estetis, melainkan etika yang lahir dari pengalaman hidup kolektif masyarakat Jawa yang memandang alam sebagai bagian dari kehidupan moral itu sendiri. Dalam horizon ini, gotong royong bukan hanya praktik sosial, melainkan ekspresi kosmis dari kesadaran bahwa kehidupan berlangsung dalam jalinan relasi yang saling menopang (Riyanto, 2022; Magnis-Suseno, 1984).
Kesadaran semacam ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Buddhadharma tidak hadir di tanah Jawa sebagai lapisan asing, melainkan ngoyot jero—mengakar dalam dan menyatu dengan laku hidup masyarakatnya. Pada masa Medang Mataram, kehadiran Borobudur bukan sekadar monumen religius, melainkan pusat kosmologi etis yang membentuk cara manusia Jawa memahami dunia dan dirinya. Integrasi ini memperkaya kearifan lokal Jawa dengan prinsip kesalingketergantungan dan tanggung jawab batin terhadap semesta, sehingga memayu hayuning bawono menemukan pijakan historis dan simboliknya yang paling kuat melalui kehadiran Borobudur (Shinta Lee, 2019; Salim Lee, 2018).
Makna dibalik Relief Borobudur
Relief Borobudur memperlihatkan laku manusia dalam jaring sebab-akibat: ngunduh wohing pakarti pada relief karmavibhaṅga; migunani tumraping liyan dalam kisah-kisah Jātaka dan Avadāna; kasampurnaning dumadi dalam narasi Lalitavistara; serta semangat ngangsu kawruh dalam Gandavyūha. Keseluruhan rangkaian ini menggambarkan bagaimana transformasi batin manusia—bukan dominasi atas alam—dipahami sebagai dasar keharmonisan dunia dan prasyarat bagi kehidupan yang ayu dan lestari (Shinta Lee, 2019).
Nilai-nilai Buddhadharma tidak hadir di tanah Jawa sebagai lapisan asing, melainkan ngoyot jero—mengakar dalam dan menyatu dengan laku hidup masyarakatnya. Pada masa Medang Mataram, kehadiran Borobudur bukan sekadar monumen religius, melainkan pusat kosmologi etis yang membentuk cara manusia Jawa memahami dunia dan dirinya. Integrasi ini memperkaya kearifan lokal Jawa dengan prinsip kesalingketergantungan dan tanggung jawab batin terhadap semesta (Shinta Lee, 2019; Salim Lee, 2018). Jika kesadaran demikian dimiliki sebagian individu. Maka bencana ekologis ini akan menjadi cermin krisis kesadaran.