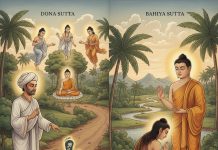Beberapa waktu lalu, saya membaca artikel ilmiah cukup menarik dari Ugo Dessi. Bukan artikel baru, karena ia sudah terbit pada 2022 lalu. Judulnya “Trajectories of East Asian Buddhism in South Africa: a comparative perspective”. Dari artikel itu, muncul pertanyaan bagaimana Buddhadharma Asia Timur sebagai agama yang lahir di Asia. Dengan akar filosofis, estetika, dan praktik yang begitu kental beradaptasi ketika tiba di bumi Afrika Selatan? Sebuah wilayah yang memiliki lanskap spiritual, sejarah kolonial, dan dinamika sosial yang sangat berbeda.
Dessi dalam artikel yang dimuat Journal of Global Buddhism tersebut. Membandingkan tiga bentuk Buddhadharma Asia Timur yang aktif di Afrika Selatan saat ini. Pertama, Dharma Centre, yang berakar pada tradisi Zen. Kedua, Soka Gakkai International (SGI) dari Jepang. Ketiga, Foguangshan, gerakan Buddhis Tiongkok yang menggabungkan aliran Chan dan Pure Land. Menariknya, meski semua menyebarkan ajaran Buddha, cara mereka beroperasi, berinteraksi dengan masyarakat lokal, dan menghadirkan ajaran tersebut ternyata sangat berbeda.
Titik Temu Buddhadharma Asia Timur dan Afrika
Salah satu temuan paling mengejutkan adalah rendahnya tingkat hibridisasi—artinya, ketiga kelompok ini hampir tidak mengadaptasi ajaran atau praktik mereka agar menyatu dengan budaya atau tradisi keagamaan Afrika Selatan. Dessi (2022: 451) mencatat bahwa ini bukan sekadar soal “modernisme Buddhis”, melainkan hasil dari beberapa faktor: fokus internal pada praktik tertentu, jarak budaya yang lebar antara Asia Timur dan Afrika, serta sejarah Buddhadharm yang masih sangat muda di negeri itu.
Lebih dari itu, ketiganya tampak tidak tertarik pada gerakan “Buddhadharma non-sektarian”—sebuah pendekatan yang justru populer di banyak negara Barat, di mana batas aliran diperlonggar demi solidaritas antarpemeluk. Di sini, identitas sektarian justru menjadi tembok: SGI dan Foguangshan misalnya, sangat menjaga kemurnian tradisi masing-masing.
Yang juga mencolok adalah minimnya interaksi dengan agama-agama lokal seperti tradisi spiritual Afrika atau bahkan gereja-gereja Kristen yang dominan. Menariknya, Dessì (2022, hlm. 451) menunjukkan bahwa ini bukan hanya soal sikap eksklusif dari pihak Buddhis, tetapi juga karena resistensi dari komunitas agama lokal yang enggan terlibat dialog lintas keyakinan.
Baca juga: Jejak Sunyi Shaolin Afrika
Titik Beda: Demokrasi, Struktur, dan Warisan Apartheid
Namun, di balik kesamaan tersebut, ada perbedaan struktural dan filosofis yang signifikan. Dharma Centre, misalnya, justru menonjol karena pendekatannya yang lebih demokratis—sesuatu yang sangat relevan di Afrika Selatan, negara yang masih menyembuhkan luka Apartheid. Struktur kepemimpinan di Dharma Centre lebih partisipatif, sementara SGI dan Foguangshan tetap mempertahankan hierarki yang ketat, mirip dengan struktur organisasi di negara asal mereka (Dessi 2022: 451).
Bagi saya, ini mengangkat pertanyaan etis: apakah model kepemimpinan yang sangat hierarkis masih sesuai di konteks pasca-kolonial yang sangat sensitif terhadap ketimpangan kekuasaan? Atau justru, apakah ketegasan struktur itu justru memberi rasa stabilitas bagi para pencari spiritual?
Globalisasi yang Tak Setara
Dessì juga menunjukkan bahwa penyebaran Buddhadharma Asia Timur di Afrika Selatan terjadi melalui empat saluran utama: misi resmi, migrasi komunitas Asia, mobilitas individu (seperti guru atau relawan), dan mediatisasi—terutama popularitas Buddhadharma di kalangan kelas menengah urban (Dessi 2022: 452). Namun, meski menyebar secara global, kehadiran mereka tetap kecil: diperkirakan hanya 2.000–3.000 orang dari total populasi 59 juta jiwa (Dessi 2022: 452).
Yang lebih penting, pola globalisasi ini cenderung satu arah: dari Asia ke Afrika, tanpa banyak ruang untuk lokalitas. Alih-alih menciptakan bentuk baru yang “Afrika Selatan”, ketiga gerakan ini cenderung mengekspor budaya dan praktik aslinya apa adanya. Dalam istilah akademik, ini bukan proses glokalisasi (global + lokal), melainkan bentuk homogenisasi budaya (Dessi 2022: 453).
Meski begitu, Dessì tidak menutup kemungkinan adanya benih-benih perubahan. Beberapa praktisi individu mulai bereksperimen: menggabungkan meditasi Zen dengan lagu-lagu tradisional, atau mengaitkan konsep karma dengan nilai-nilai komunitas setempat. Namun, apakah ini awal dari “South-Africanization” Buddhadharma Asia Timur, atau hanya anomali kecil yang tak bertahan lama? Waktu yang akan menjawab.
Mempertanyakan Pilihan Kausalya
Sebagai seseorang yang memandang penyebaran dharma melalui lensa kausalya—kebijaksanaan dalam memilih metode sesuai konteks sosial dan budaya—saya tak bisa tak bertanya: di mana kausalya ini dalam konteks Afrika Selatan? Apakah ketiga gerakan tersebut terlalu fokus pada “kesetiaan pada tradisi” hingga lupa bahwa ajaran Buddha pada dasarnya selalu bersifat kontekstual? Selalu beradaptasi sehingga kita sekarang bisa menikmati keindahan dalam keberagaman? ada Chinese Buddhism, Japanese Buddhism, Javanese Buddhism, bahkan sedang dalam proses American dan Australian Buddhism.
Artikel Dessi mengingatkan kita bahwa globalisasi agama bukanlah proses netral. Ia membawa serta budaya, kekuasaan, dan asumsi-asumsi yang tak selalu cocok dengan tanah baru. Dan mungkin, ke depannya, tantangan terbesar bagi Buddhadharma Asia Timur di Afrika Selatan bukanlah bagaimana menjangkau lebih banyak orang—tapi bagaimana menjadi bagian dari dunia yang mereka masuki, bukan sekadar tamu yang datang membawa koper penuh doktrin.@Eddy Setiawan