Sebagai etika publik, perjumpaan antara Buddhadharma dan falsafah Jawa membuka kemungkinan lahirnya etika ekologis Nusantara yang tidak bersifat tambal-sulam, melainkan berakar pada tradisi luhur yang telah lama hidup di wilayah ini. Etika ini memandang krisis ekologis bukan semata sebagai persoalan teknis, tetapi sebagai krisis relasional—rusaknya hubungan antara manusia, alam, dan tata nilai yang menopang keduanya (Kaza & Kraft, 2000; Loy, 2010).
Dosa/Dvesa: Penolakan Membuta Terhadap Akal Sehat
Jika lobha dan taṇhā menjelaskan dorongan kerakusan dan rasa tak berkecukupan, serta moha–avidyā menjelaskan kebingungan struktural. Maka dosa/dveṣa (aversion) menyingkap dimensi lain dari krisis ekologis yang kerap diabaikan. Yaitu penolakan aktif terhadap koreksi, kritik, dan refleksi etis. Dalam Buddhadharma, dosa bukan sekadar kemarahan emosional. Melainkan sikap batin yang menolak kenyataan yang tidak menyenangkan. Terutama kenyataan bahwa suatu tindakan telah melahirkan penderitaan (AN 3.69 – Akusala-mūla Sutta). Menggali pesan leluhur: Bencana Ekologi Aceh-Sumatra.
Dalam konteks kebijakan publik, dosa menjelma sebagai penolakan rezim terhadap masukan akal sehat dari para cendekiawan, ilmuwan lingkungan, masyarakat adat, dan pemerhati ekologi. Keengganan untuk melakukan introspeksi, serta penolakan untuk meninjau ulang keputusan politik. Keputusan yang keliru dengan dampak destruktif nyata. Dalam bahasa falsafah Jawa, sikap ini dapat dibaca sebagai ‘selak marang pepeling. Sikap penolakan terhadap nasihat. Dan bentuk hilangnya kesadaran reflektif yang seharusnya menuntun laku kuasa.
Lebih jauh, dosa termanifestasi ketika ‘kritik etis’ justru oleh rezim dilabeli sebagai ‘ancaman terhadap stabilitas.’ Dan para pejuang lingkungan diposisikan sebagai ‘musuh status quo’ yang mengganggu kepentingan oligarkis. Buddhadharma mengingatkan. Bahwa dosa memutus relasi welas asih dan membekukan kemampuan belajar kolektif. Ia menutup ruang dialog dan menghalangi kemungkinan koreksi diri (SN 12.1 – Paṭiccasamuppāda Sutta).
Ketika dosa bersenyawa dengan lobha dan moha. Maka kebijakan tidak lagi diarahkan untuk mengurangi penderitaan. Melainkan untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan. Sekalipun harus mengorbankan keselamatan rakyat dan keberlanjutan kehidupan. Dalam cakrawala memayu hayuning bawono, inilah bentuk kegagalan etis paling serius. Ketika kekuasaan kehilangan kemampuan eling lan waspada. Dan dunia dibiarkan rusak demi mempertahankan rasa benar diri dan kepentingan sempit.
Oligarki dan Kelesah Struktural
Ketika lobha – ketamakan, taṇhā – kehausan, dan moha – sesat nalar bersenyawa dengan kepentingan oligarki dan kapital besar. Maka penderitaan tidak lagi bersifat insidental, melainkan terstruktur. Buddhadharma menyebut keadaan ini sebagai kelesah (kilesa) yang berlipat ganda. Suatu ‘kondisi batin yang sangat kacau dan keruh.’ Tetapi justru diproduksi ulang dan dipertahankan ‘kekeruhannya’ melalui sistem yang korup. Dalam kerangka ini, bencana ekologis bukan sekadar “musibah alam.” Melainkan buah dari tindakan kolektif:
“Makhluk adalah pemilik tindakannya, pewaris tindakannya.”
(MN 135 – Cūḷakammavibhaṅga Sutta).
Bahasa ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban. Akan tetapi menarik tanggung jawab moral ke ‘pusat pengambilan keputusan – rezim penguasa’ hari ini.
Memayu Hayuning Bawono sebagai Etika Kebijakan Alternatif
Falsafah Jawa memayu hayuning bawono menawarkan horizon kebijakan yang berlawanan secara mendasar. Ia tidak bertanya: apa yang bisa diambil? Melainkan: apa yang harus dijaga agar dunia tetap ayu dan lestari? Dalam bahasa Buddhadharma, ini sejalan dengan tindakan yang selaras dengan Dhamma (sammā). Tindakan yang mengurangi penderitaan, bukan memperpanjangnya.
“Periksa, apakah tindakan ini membawa penderitaan bagi dirimu, bagi orang lain, atau bagi keduanya.” (MN 61 – Ambalaṭṭhikārāhulovāda Sutta). Jika prinsip ini diterjemahkan ke dalam kebijakan publik. Konsekuensinya setiap regulasi ekologis semestinya diuji dengan satu pertanyaan mendasar. Apakah kebijakan ini melindungi kehidupan, atau justru mempercepat penderitaan?
Menggali Pesan Leluhur: Etika Ekologis dan Tradisi Luhur
Sebagai etika publik, perjumpaan antara Buddhadharma dan falsafah Jawa membuka kemungkinan lahirnya etika ekologis Nusantara yang tidak bersifat tambal-sulam, melainkan berakar pada tradisi luhur yang telah lama hidup di wilayah ini. Etika ini memandang krisis ekologis bukan semata sebagai persoalan teknis, tetapi sebagai krisis relasional—rusaknya hubungan antara manusia, alam, dan tata nilai yang menopang keduanya (Kaza & Kraft, 2000; Loy, 2010).
Pertama, kesadaran akan jaringan kehidupan menjadi fondasi etis utama. Kesalingketergantungan (iddapaccayatā) mengajak manusia melihat bahwa bencana bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan buah dari relasi-relasi yang timpang dan eksploitatif. Dalam kerangka ini, banjir dan longsor di Aceh–Sumatera Utara adalah cermin dari relasi manusia–alam yang telah lama terluka (SN 12.1 – Paṭiccasamuppāda Sutta).
Kedua, gotong royong dipahami sebagai spiritualitas kolektif, bukan sekadar mekanisme sosial darurat. Gotong royong adalah praktik nyata dari memayu hayuning bawono: bertindak bersama untuk menjaga keseimbangan kehidupan sebelum krisis terjadi, bukan hanya saling menolong setelah bencana melanda. Dalam konteks kebijakan, ini menuntut partisipasi komunitas lokal, penghormatan terhadap pengetahuan adat, dan perlindungan nyata terhadap kelompok rentan. Menggali pesan leluhur mengenai gotong royong, tentu bukan perkara yang sulit.
Ketiga, etika ekologis Nusantara menegaskan tanggung jawab dalam tindakan kolektif. Buddhadharma mengingatkan bahwa makhluk adalah pemilik tindakannya dan pewaris akibatnya (MN 135 – Cūḷakammavibhaṅga Sutta). Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk menarik tanggung jawab moral ke pusat-pusat pengambilan keputusan (rezim) yang selama ini kerap luput dari pertanggungjawaban etis.
Keempat, perlindungan terhadap komunitas rentan—petani, masyarakat adat, nelayan, dan warga miskin kota—menjadi ukuran konkret dari etika ekologis. Dalam Buddhadharma, kepedulian (mettā dan karuṇā) tidak bersifat abstrak, melainkan menuntut keberpihakan nyata pada mereka yang paling terdampak. Dalam falsafah Jawa, prinsip tepa selira menegaskan bahwa penderitaan pihak lain tidak pernah terpisah dari diri kita sendiri. Inilah mengapa menggali pesan leluhur relevan dengan kondisi saat ini.
Dibutuhkan Keberanian Melakukan Koreksi
Dengan demikian, etika ekologis Nusantara bukan sekadar wacana normatif, melainkan ajakan untuk membangun kembali orientasi hidup dan kebijakan yang berpihak pada kehidupan. Ia menuntut keberanian untuk mengoreksi arah pembangunan, membatasi kerakusan yang dilembagakan, dan menata ulang relasi manusia–alam dalam horizon tanggung jawab bersama.


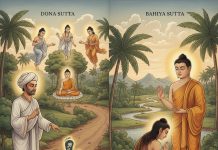











[…] Kembali ke bagian 3/4 Menggali Kembali Pesan Leluhur: Bencana Ekologi Aceh dan Sumatra […]
[…] Bersambung ke bagian 3/4 Menggali Pesan Leluhur… […]