
Alih-alih melakukan moratorium dan evaluasi menyeluruh atas model pembangunan berbasis perambahan hutan, negara justru bersiap mereproduksi skema kerusakan ekologis yang sama di wilayah lain yang secara ekologis dan sosial jauh lebih rentan. Sikap ini menunjukkan ketidakpekaan struktural terhadap prinsip kesalingketergantungan serta mengungkap watak pembangunan yang lebih setia pada kepentingan oligarki dan kapital ekstraktif ketimbang keselamatan rakyat dan keberlanjutan kehidupan (WALHI, 2023; Kompas.com, 2025).
Kritik terhadap Respons Kebijakan: Politik dan Lobha Dosa Moha
Seiring bencana yang meluas, kritik terhadap respons pemerintah pun menguat. Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa situasi dianggap terkendali dan kehidupan dapat kembali normal dalam beberapa bulan. Mencerminkan jarak yang serius antara bahasa kebijakan dan realitas penderitaan warga terdampak. Pernyataan semacam ini bukan sekadar problem komunikasi. Melainkan indikasi kegagalan etis negara dalam membaca penderitaan rakyat sebagai akibat langsung dari pilihan-pilihan kebijakan sebelumnya. (Kompas.com, 2025).
Lebih jauh, wacana Presiden Prabowo mengenai perluasan perkebunan kelapa sawit di Papua demi produksi bahan bakar. Memperlihatkan dengan gamblang kegagalan rezim dalam menarik pelajaran dari bencana Aceh dan Sumatera. Alih-alih melakukan moratorium dan evaluasi menyeluruh atas model pembangunan berbasis perambahan hutan. Negara justru bersiap mereproduksi skema kerusakan ekologis yang sama di wilayah lain. Wilayah yang secara ekologis dan sosial jauh lebih rentan. Sikap ini menunjukkan ketidakpekaan struktural terhadap prinsip kesalingketergantungan. Serta mengungkap watak pembangunan yang lebih setia pada kepentingan oligarki dan kapital ekstraktif. Ketimbang keselamatan rakyat dan keberlanjutan kehidupan (WALHI, 2023; Kompas.com, 2025).
Sepertinya presiden masih belum cukup menyaksikan kehancuran yang diderita Aceh dan Sumatra. Yang seharusnya dapat menjadi cermin kegagalan rezim ini menjaga keselamatan rakyat dari bencana ekologis. Bencana akibat perusakan hutan yang seolah dilegalkan. Lalu dengan tanpa beban dan tidak peka, rezim bersiap menciptakan kondisi kerusakan lanjutan di Papua.
Kebijakan yang mengutamakan ekspansi monokultur tanpa memperhatikan dampak ekologis jangka panjang. Hanya menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah masih terjebak pada logika ekonomi semata. Logika yang mengabaikan prinsip kesalingketergantungan yang fundamental. Ketidaksensitifan semacam ini mengindikasikan kurangnya penyadaran akan keterhubungan antara keputusan politik dan dampak ekologis. Hal yang pada akhirnya berimbas pada keselamatan rakyat, bahkan nyawa mereka.
Lobha Dosa Moha: Akar Beracun Kebijakan yang Merusak Alam
Dalam Buddhadharma, penderitaan tidak pernah dipahami sebagai peristiwa kebetulan. Ia selalu memiliki sebab, dan sebab itu berakar pada kondisi batin. Sang Buddha merumuskan akar penderitaan itu secara ringkas namun tegas sebagai lobha (rasa tidak berkecukupan dan kerakusan), dosa (penolakan), dan moha (kebingungan atau keliru mengerti). Ketiganya disebut sebagai akar tidak-bajik (akusala-mūla) atau trivisa – tiga racun.
“Ada tiga akar tidak-bajik: lobha, dosa, dan moha.”
(AN 3.69 – Akusala-mūla Sutta)
Dalam konteks bencana ekologis di Aceh dan Sumatera Utara, tiga akar negatif atau tiga racun (trivisa) batin ini tidak hanya hadir pada level individual, tetapi telah menjelma menjadi rasionalitas kebijakan dan kerangka pembangunan.
Lobha: Ketidakcukupan yang Dilembagakan
Lobha dalam pengertian Buddhadharma bukan sekadar keserakahan vulgar, melainkan perasaan eksistensial bahwa apa yang ada tidak pernah cukup. Ketika rasa tidak berkecukupan ini menjadi dasar kebijakan, alam diposisikan semata sebagai resource base—basis sumber daya yang harus terus diekstraksi demi pertumbuhan ekonomi.
Dalam bahasa kebijakan publik, lobha menjelma sebagai orientasi pertumbuhan tanpa batas (growth imperative), Indikator keberhasilan yang semata berbasis produksi dan output, serta pengabaian daya dukung ekologis (carrying capacity).
>Terkait ini Buddha telah mengingatkan secara eksplisit bahwa lobha tidak pernah membawa kesejahteraan, melainkan penderitaan lanjutan:
“Dari lobha muncul penderitaan; dari lobha muncul rasa takut.”
(Dhp 216)
Banjir bandang dan longsor yang berulang justru memperlihatkan paradoks kebijakan berbasis lobha: semakin alam dieksploitasi atas nama kesejahteraan, semakin besar penderitaan yang ditanggung masyarakat.
Taṇhā: Dorongan Kebijakan yang Tidak Pernah Puas
Jika lobha adalah rasa tidak berkecukupan, maka taṇhā adalah dorongan untuk terus memuaskannya. Taṇhā bekerja melalui logika “harus lebih”: lebih banyak energi, lebih luas lahan industri, lebih tinggi produksi. Dalam kerangka kebijakan, taṇhā hadir sebagai Obsesi terhadap ekspansi, Narasi ketertinggalan yang menjustifikasi perusakan, dan pengabaian prinsip kehati-hatian ekologis (precautionary principle).
Buddha menegaskan bahwa taṇhā adalah sumber langsung penderitaan kolektif:
“Inilah asal mula penderitaan: taṇhā yang menimbulkan kelahiran kembali, disertai kenikmatan dan nafsu, yang mencari kepuasan di sana-sini.”
(SN 56.11 – Dhammacakkappavattana Sutta)
Ketika taṇhā (kehausan, kerakusan, ketamakan, rasa tak berkecukupan) menjadi motor kebijakan, negara terjebak dalam lingkaran produksi–kerusakan–penanggulangan, tanpa pernah menyentuh akar masalahnya.
Moha dan Avidyā: Kebingungan yang Melahirkan Keputusan Keliru
Namun akar terdalam dari lobha dan taṇhā adalah moha atau avidyā—keliru mengerti. Dalam Buddhadharma, avidyā bukan sekadar kurang informasi, melainkan gagal memahami kesalingketergantungan (iddapaccayatā).
“Karena tidak mengetahui dan tidak memahami secara benar, makhluk-makhluk ini terjerat dan berputar dalam penderitaan.” (SN 12.1 – Paṭiccasamuppāda Sutta)
Dalam bahasa kebijakan publik, avidyā termanifestasi sebagai pemisahan ekonomi dari ekologi, pemisahan pembangunan dari keselamatan rakyat, dan pemisahan keputusan dari dampak jangka panjangnya. Avidyā membuat kebijakan tampak sah secara prosedural, tetapi gagal secara etis dan ekologis. Negara hanya hadir sebagai pengelola izin yang miskin integritas, bukan penjaga kehidupan yang mengemban amanat penderitaan rakyat.
Eko Nugroho R (Peneliti Institut Nagarjuna)

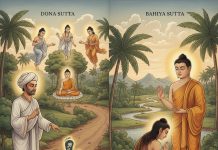











[…] Bersambung ke bagian 2 Loba Dosa Moha… […]