Sebuah artikel ilmiah di jurnal pendidikan sejarah bernama Widya Winayata menarik perhatian saya. Terutama karena artikel yang ditulis oleh Maharani, Purnawati & Martayana (2025) tersebut mengupas sebuah vihara yang saya kenal sejak kanak-kanak. Konco Blahbatuh, demikian keluarga kami biasa menyebutnya. Sebuah vihara yang letaknya paling unik, yakni di posisi bawah sebuah jembatan kuno era kolonial dan dekat aliran sungai. Nama resminya Vihara Amurva Bhumi.
Atap vihara ini hampir sejajar dengan jalanan, yang sekarang sudah lebar dan jembatannya pun baru. Hal lain yang sulit dilupakan adalah, kuliner tahu yang khas. Jika suata hari anda berkunjung, tentu wajib mencobanya. Tahu tersebut biasa kami beli setelah sembahyang ce it atau cap go. Atau orang Tionghoa Bali menyebutnya Tilem dan Purnama, mengikut istilah setempat. Uniknya, meski sama-sama menggunakan istilah Purnama dan Tilem, tapi tak jarang terdapat perbedaan waktu 1 hari antara umat Hindu dan Buddha.
Kembali ke soal artikel ilmiahnya. Ketiga penulis menyajikan artikel dengan judul Menyongsong Harmoni: Pergulatan Sejarah, Akulturasi, dan Potensi Vihara Amurva Bhumi Blahbatuh Gianyar sebagai Sumber Belajar Sejarah SMA. Para penulis memberikan gambaran penting tentang dinamika identitas keagamaan komunitas Tionghoa di Bali. Penelitian ini mengungkap bahwa Vihara Amurva Bhumi, berakar pada keberadaan Kim Sae Bio atau Bio Singa Mas yang waktu pendiriannya tidak diketahui. Diperkirakan sekira 1800-an, dengan dasar penemuan bong pay (nisan) tertua di pemakaman komunitas Tionghoa terdekat. Baru pada era Orde Baru namanya diganti menjadi Vihara Amurva Bhumi (Maharani, Purnawati, & Martayana, 2025: 46).
Kritik terhadap Artikel terkait Vihara Amurva Bhumi
Sayangnya para penulis tidak mencoba mengeksplorasi lebih jauh mengenai Singa Emas. Padahal Singa Emas adalah salah satu metafora paling terkenal dari aliran Huayan (Avataṃsaka). Salah satu aliran Agama Buddha dengan sistem filsafat paling kompleks di Tiongkok, yang sudah berkembang sejak masa Dinasti Tang (618-907). Aliran ini berakar pada Avataṃsaka-sutra yang menekankan keterjalinan total seluruh fenomena (dharmadhatu), melalui prinsip saling-penembusan dan saling-mencakup tanpa hambatan.
Puncak perumusan intelektualnya terjadi pada masa Bhiksu Fa-tsang (643–712). Patriark ketiga Huayan, yang berperan sebagai penasihat keagamaan istana dan kemudian ditetapkan sebagai Guoshi (Guru Negara). Tak heran karena salah seorang muridnya adalah Wu Zetian. Satu-satunya perempuan yang menjadi Kaisar penuh di Tiongkok kuno, dan pendiri Dinasti Zhou (690–705). Relasi tersebut menyebabkan Agama Buddha memiliki patronase politik yang sangat kuat. Fa-tsang memanfaatkannya untuk menyajikan penjelasan sistematik tentang doktrin Huayan.
Di bawah perlindungan Wu Zetian, Bhiksu Fa-tsang menyusun sejumlah karya penting, termasuk Jin shizi zhang (Bab tentang Singa Emas). Ia menggunakan patung singa emas sebagai ilustrasi hubungan antara esensi dan bentuk. Sekaligus sebagai pintu masuk untuk memahami kosmologi Huayan lebih lanjut, seperti metafora Jaring Permata Indra. Pertemuan intelektual antara Fa-tsang dan Wu Zetian ini menandai masa ketika Huayan mencapai status resmi dan berkembang menjadi salah satu aliran filosafat paling berpengaruh dalam sejarah Buddhisme Tiongkok.
Kim Sae Bio memiliki Makna Filosofis Mendalam
Maka, pendiri atau pemberi nama Kim Sae Bio tentu bukanlah orang sembarangan. Kemungkinan seorang intelektual Buddhis dari aliran Huayan. Bisa saja seorang bhiksu terpelajar atau cendikiawan Buddhis awam. Alasannya, karena nama Singa Emas sangat langka ditemukan sebagai nama bio. Umumnya, nama tempat ibadah Buddhisme Tionghoa, dikaitkan dengan dewata utama atau tuan rumah. Misal Kwan Im Teng jika tuan rumahnya Bodhisattva Avalokitesvara. Atau Ho Tek TJeng Sin kalau tuan rumahnya dewa bumi, sebagaimana tuan rumah di Bio Singa Emas.
Para penulis tampaknya lebih tertarik pada pemisahan antara dhammasala di satu sisi sebagai tempat ibadah Buddha Theravada. Dan baktisala di sisi lain sebagai tempat pemujaan terhadap Hok Tek Ceng Sin (Dewa Bumi). Penelitian ini menekankan bahwa transformasi dari bio menjadi vihara terutama dipicu oleh kebijakan Orde Baru yang menuntut komunitas Tionghoa memilih salah satu dari lima agama resmi, sehingga mereka memilih agama Buddha sebagai identitas formal, sambil tetap mempertahankan ritual tradisional mereka (Maharani, Purnawati, & Martayana, 2025: 44–45).
Akulturasi, menurut penulis, terwujud dalam arsitektur, ritual (seperti pelaksanaan mecaru ala Bali dalam perayaan Sejit), bentuk persembahan (mirip gebogan dan penggunaan canang sari), serta kesenian (gamelan oleh Sekaa Gong Gita Pertiwi). Vihara ini pun diusulkan sebagai sumber belajar sejarah SMA, terutama untuk materi pemerintahan Orde Baru dan pengembangan Profil Pelajar Pancasila (Maharani, Purnawati, & Martayana, 2025: 52–55).
Akulturasi Bukanlah Fenomena Modern Indonesia
Meskipun temuan Maharani dkk. (2025) akurat dalam menggambarkan konteks politik Orde Baru, narasi akulturasi yang mereka sajikan berisiko mendehistorisasi akar agama Buddha itu sendiri. Mereka seolah mengandaikan bahwa “akulturasi antara agama Buddha dan tradisi Tionghoa” baru terjadi di Indonesia, bahkan baru dimulai pada abad ke-20 akibat tekanan politik Orde Baru.
Padahal, seperti dijelaskan secara komprehensif oleh Choe & Son (2023) dalam Protocols of Conversion: Indigenous Gods and Eminent Monks in East Asian Buddhism, proses integrasi antara ajaran Buddha dan dewa-dewa lokal telah berlangsung sejak abad pertama Masehi di Tiongkok kuno. Ketika Buddhisme memasuki Tiongkok, ajaran ini tidak hadir sebagai sistem doktrinal yang “murni” dan terisolasi, melainkan segera berdialog dengan kosmologi lokal—termasuk pemujaan leluhur, dewa bumi, dan roh alam. Mengembangkan kosmologi Buddhis yang khas Tiongkok.
Dewa sebagai Pelindung Dharma
Salah satu pola kunci dalam proses ini, menurut Choe & Son, adalah bahwa dewa-dewa lokal memperoleh legitimasi Buddhis ketika mereka berinteraksi erat dengan para bhiksu agung. Catatan mengenai para bhiksu agung ini diantaranya terdokumentasi dalam Gaoseng zhuan (abad ke-6) dan Xu Gaoseng zhuan (abad ke-7). Dalam kedua karya tersebut, dewa-dewa lokal digambarkan meminta sila Buddhis (Choe & Son, 2023: 2). Mereka bahkan disebut jieshen (dewa penerima sila) dan berperan sebagai dharmapala atau pelindung Dharma. Bukan sebagai entitas “non-Buddhis” yang kemudian ditoleransi, melainkan sebagai bagian integral dari tatanan Buddhis yang tersinifikasi (Choe & Son, 2023: 5).
Fakta historis ini menunjukkan bahwa, apa yang orang Indonesia sebut sebagai kelenteng. Sejak awal bukanlah “tempat ibadah non-agama” atau “tempat ibadah tiga agama” yang kemudian di-Buddha-kan di Indonesia. Melainkan manifestasi dari Chinese Buddhism—bentuk Mahayana yang telah disinifikasi dan secara alami menyerap praktik agama rakyat Tiongkok. Mentranformasi dan mengintegrasikannya dengan pemujaan terhadap Bodhisattva (seperti Guanyin, Ti Zhang Wang, Sangharama dan sebagainya), Mahasatva dan dewa-dewa. Dengan kata lain, Kim Sae Bio sejak awal sangat jelas karakteristik Buddhisnya.
Narasi Orde Baru dan Simplifikasi Populer: Buddhanisasi
Yang terjadi pada masa Orde Baru bukanlah “awal akulturasi”, melainkan restrukturisasi identitas keagamaan dalam kerangka negara modern. Komunitas Tionghoa Blahbatuh tidak meninggalkan keyakinan mereka. Responnya adalah adaptasi, dengan menyesuaikan bentuk luar keagamaan sesuai tuntutan aturan. Dari yang semula lebih bersifat Mahayana yang kuat karakteristik Tionghoanya, ke Theravada yang lebih dapat diterima penguasa saat itu. Namun, inti religius mereka, termasuk pemujaan Hok Tek Ceng Sin, dan tata cara sembahyangnya tidak berubah.
Sayangnya, narasi seperti yang disajikan Maharani, Purnawati & Martayana (2025)—dan memang sudah menjadi narasi umum di Indonesia—cenderung menyederhanakan kompleksitas ini. Dengan menempatkan Kim Sae Bio sebagai “Tionghoa” lalu Agama Buddha masuk ketika masa orde baru. Padahal, seperti diingatkan oleh Choe & Son (2023), “apa yang disebut sebagai ‘kepercayaan asli’ merupakan sumber bagi inovasi dan penggabungan gagasan baru dalam sejarah Buddhisme Asia Timur” (Choe & Son, 2023: 9). Dengan kata lain, difusi unsur lokal ke dalam Agama Buddha adalah bagian esensial dari pola Agama Buddha berakar di suatu wilayah.
Baca juga: Kelenteng: Tempat Ibadah Agama Buddha Tradisi Tionghoa
Mengabaikan lapisan sejarah ini—yaitu sinifikasi di Tiongkok (abad ke-1–7 M) dan transplantasi Chinese Buddhism ke Nusantara (sejak abad ke-15)—akan menghasilkan pemahaman yang simplistis dan ahistoris. Maka, meskipun transformasi pada masa Orde Baru penting untuk dipahami—terutama dalam konteks pendidikan sejarah SMA—ia hanya lapisan terakhir dari proses akulturasi yang telah berlangsung selama ribuan tahun di Tiongkok kuno.
Jangan Lupakan Akar Sejarah
Vihara Amurva Bhumi Blahbatuh memang layak diapresiasi sebagai ruang harmoni antarbudaya. Namun, agar apresiasi itu tidak berubah menjadi pengaburan sejarah, kita perlu menempatkannya dalam konteks sejarah agama Buddha global.
Kelenteng bukanlah “tempat ibadah non-resmi atau sekedar tradisi” yang kemudian disesuaikan. Ia adalah bagian sah dan otentik dari tradisi Buddhisme Asia Timur. Tradisi yang sejak awal telah mempraktikkan inklusivitas, dialog, dan transformasi kreatif. Dan pada akhirnya, seperti ditunjukkan oleh para bhiksu ternama dalam Xu Gaoseng zhuan, kehadiran dewa lokal bukanlah ancaman terhadap Dharma, melainkan bukti bahwa Dharma mampu menyerap, mentransformasi, dan mengembangkan pemaknaan.@Eddy Setiawan.
Bacaan Lanjutan
Choe, J & Son, J 2023, ‘Protocols of Conversion: Indigenous Gods and Eminent Monks in East Asian Buddhism,’ Religions, Vol. 14, No. 7, 838. DOI: https://doi.org/10.3390/rel14070838.
Maharani, PEA; Purnawati, DMO; Martayana, IPHM 2025, ‘Menyongsong Harmoni: Pergulatan Sejarah, Akulturasi, dan Potensi Vihara Amurva Bhumi Blahbatuh Gianyar sebagai Sumber Belajar Sejarah SMA,’ Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 12, No. 1, pp 39–55.


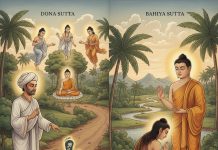











[…] Baca juga: Vihara Amurva Bhumi Blahbatuh: Singa Emas yang Terlupakan […]